
Hukum dan Kekuasaan: Siapa Menundukkan Siapa?
Oleh: Diaz

Hukum dan Kekuasaan: Siapa Menundukkan Siapa?
RATASTV – Sejak lama, hubungan antara hukum dan kekuasaan selalu menjadi perdebatan panjang. Hukum hadir sebagai aturan main yang disepakati untuk menjaga ketertiban, memberi rasa keadilan, dan melindungi rakyat. Kekuasaan hadir sebagai instrumen untuk menjalankan aturan itu. Idealnya, hukum berdiri di atas kekuasaan, sehingga siapa pun yang berkuasa harus tunduk padanya. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa sering kali hukum justru menjadi alat yang diperalat kekuasaan.
Kita sering mendengar adagium “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Kalimat sederhana itu mencerminkan realitas sehari-hari. Seorang pejabat tinggi yang terjerat kasus bisa menempuh berbagai cara untuk lolos: mulai dari lobi politik, permainan opini, hingga tekanan terhadap penegak hukum. Sebaliknya, rakyat kecil yang mencuri barang sepele dapat dihukum tanpa ampun. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya tegak berdiri, melainkan masih goyah di hadapan kekuasaan.
Padahal, secara prinsip, hukum adalah pagar yang membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Kekuasaan tanpa kendali hukum akan melahirkan tirani. Sejarah dunia membuktikan bagaimana rezim otoriter selalu memanipulasi hukum untuk membenarkan langkah-langkahnya. Indonesia pun pernah mengalaminya pada masa Orde Baru, ketika hukum lebih sering digunakan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah ketimbang melindungi hak rakyat.
Namun, kita juga tidak bisa menafikan bahwa hukum tanpa kekuasaan hanyalah teks mati. Undang-undang bisa setebal apa pun, aturan bisa disusun serapih mungkin, tetapi tanpa kekuasaan yang menegakkan, semuanya hanya ilusi. Di sinilah paradoksnya: hukum membutuhkan kekuasaan untuk hidup, tetapi sekaligus harus mengendalikan kekuasaan agar tidak liar.
Reformasi 1998 membawa harapan besar bahwa prinsip rule of law akan benar-benar terwujud. Konstitusi kita menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, hukumlah yang seharusnya menjadi panglima. Tetapi perjalanan lebih dari dua dekade reformasi memperlihatkan jalan panjang yang penuh liku. Setiap kali kasus besar muncul, terutama yang melibatkan elit politik atau pejabat negara, publik selalu kembali bertanya: apakah hukum akan berdiri tegak, atau justru kembali tunduk pada tekanan kekuasaan?
Korupsi, misalnya, adalah contoh nyata bagaimana relasi hukum dan kekuasaan diuji. Ketika pelaku berasal dari kalangan bawah, proses hukumnya berjalan cepat dan tanpa kompromi. Namun, ketika pelaku adalah pejabat berpengaruh, penegakan hukum sering kali berbelit-belit. Tidak jarang prosesnya berhenti di tengah jalan, atau berakhir dengan hukuman ringan yang tidak sebanding dengan kerugian negara. Pola ini berulang, sehingga masyarakat semakin pesimis terhadap keadilan.
Untuk keluar dari lingkaran ini, Indonesia tidak cukup hanya memperbaiki teks hukum. Kita perlu membangun budaya hukum yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama, bukan sekadar kepatuhan formal. Lembaga peradilan harus benar-benar independen, aparat penegak hukum harus berani menolak intervensi politik, dan masyarakat harus terus kritis mengawasi jalannya hukum. Tanpa itu semua, hukum akan terus dipermainkan.
Montesquieu pernah mengingatkan, “Setiap orang yang memegang kekuasaan cenderung menyalahgunakannya.” Karena itu, kekuasaan perlu dibatasi, dan pembatas itu adalah hukum. Pernyataan ini relevan sekali dengan kondisi kita hari ini. Demokrasi tidak akan berarti apa-apa jika hukum hanya menjadi pelayan kekuasaan, bukan pengendali.
Pada akhirnya, keseimbangan antara hukum dan kekuasaan adalah kunci. Kekuasaan memberi energi bagi hukum untuk dijalankan, sementara hukum memberi arah agar kekuasaan tidak melenceng. Ketika hukum mampu menundukkan kekuasaan, barulah cita-cita negara hukum yang sesungguhnya tercapai: keadilan untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.
Oleh: Aulia Halsa
Founder Pajak Literasi
Berita Terkait
- Keluarga Besar Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Mengucapkan Selamat Memperingati HUT IPPAT ke-38
- Dialog Presiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa Bahas Reformasi, Hukum, dan Persatuan
- KPK Gelar Lelang Barang Rampasan Negara, Aanwijzing 11 September 2025
- Ojol dan Tokoh Masyarakat Tangsel Gelar Aksi Damai di DPRD, Tegaskan Tolak Anarkisme
- Patroli Gabungan Skala Besar di Tangsel, Benyamin Pastikan Rasa Aman Warga
Mungkin anda suka
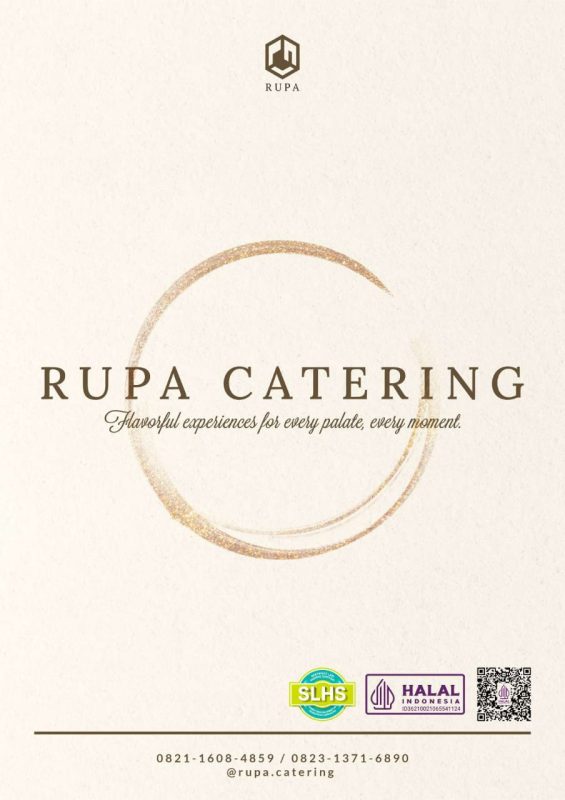
Terpopuler














