
Moratorium Kekuasaan POLRI dan Luka Kolektif Bangsa
Oleh: Diaz

Moratorium Kekuasaan POLRI dan Luka Kolektif Bangsa
RATASTV – Pada Jumat pagi, saya tersentak. Semalaman saya tak membuka gawai, dan begitu menyalakannya, kabar duka itu menyergap: seorang pemuda berusia 21 tahun, driver ojek online yang ikut turun aksi, meregang nyawa di Pejompongan. Hati saya tercekat, sebab kabar itu seakan dekat sekali saya pernah merasakan keduanya, turun ke jalan untuk aksi (sewaktu massa mahasiswa), dan juga mengojek demi hidup. Maka luka itu bukan sekadar berita, melainkan sesuatu yang mengetuk langsung ke dada. Tangan saya bergetar diatas meja kerja, sayapun men-sesapi secangkir teh tarik panas untuk menenangkan diri.
Sejenak terlintas, pertanyaan kembali mengemuka: masihkah kita percaya pada Polri? Apakah institusi ini, yang seharusnya menjadi pelindung, benar-benar bisa direformasi, atau justru sudah terlalu rusak hingga hanya melahirkan luka baru ?. Joseph Schumpeter, dalam teorinya Creative Destruction, mengatakan bahwa suatu lembaga yang penuh dengan masalah sering kali tidak bisa diperbaiki karena budaya buruknya sudah mengakar. Akankah POLRI harus mengambil jalan yang sama ? membubarkan diri .
Sejarah dunia mencatat, ada bangsa yang berani mengambil keputusan radikal. Irak pernah membubarkan seluruh kepolisiannya pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein. Georgia, di bawah Presiden Mikheil Saakashvili, membubarkan kepolisian lalu lintasnya karena sudah terlalu sarat dengan korupsi, lalu membangun kembali institusi baru dari nol. Tapi, keberanian semacam itu selalu dibayar mahal, penuh risiko, dan tidak jarang menimbulkan kekacauan baru.
Apa jadinya bila Polri bubar? Siapa yang menjaga jalanan, pelabuhan, bandara, dan desa-desa jauh di perbatasan? Kita bisa saja berkata, “TNI ambil alih, Satpol PP turun tangan sementara.” Tapi bukankah itu membuka ruang bagi bahaya baru? Bayangkan militer kembali menguasai ruang sipil, bayangkan aparat tanpa kontrol sipil yang kuat. Tidakkah sejarah telah memberi kita pelajaran tentang masa-masa gelap itu?
Indonesia, tentu, tidak bisa serta-merta mengambil langkah serupa. Kita sedang menuju cita-cita menjadi negara maju, dan membubarkan Polri bisa berarti membuka pintu kekosongan kekuasaan, yang justru berbahaya bagi stabilitas negeri ini. Maka, apakah satu-satunya jalan adalah pasrah pada kenyataan? Tidak.
Ada pilihan lain, yang mungkin lebih masuk akal: sebuah moratorium kekuasaan Polri. Sebuah jeda. Sebuah rem darurat bagi institusi yang lajunya sudah terlalu liar. Moratorium bukan berarti membubarkan, melainkan menghentikan sementara sebagian kewenangan yang paling rawan disalahgunakan terutama kewenangan represif terhadap massa aksi, serta fungsi intelijen yang kerap berubah menjadi alat pembungkaman suara rakyat.
Dalam jeda ini, fungsi-fungsi tertentu bisa dialihkan atau diawasi secara ketat oleh lembaga independen sipil, kejaksaan, bahkan kerja terbatas bersama TNI yang tetap dikontrol oleh konstitusi. Tujuannya sederhana: memberi ruang untuk refleksi, evaluasi, dan restrukturisasi mendalam. Sebab tanpa jeda, tanpa penghentian aliran kuasa itu, Polri hanya akan terus melaju di atas rel yang sama rel yang penuh darah dan air mata rakyat.
Merujuk data Komnas HAM, sepanjang lima tahun terakhir tercatat 3.714 kasus pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian. Artinya, rata-rata hampir 750 kasus per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah luka kolektif. Ia adalah anak yang kehilangan ayah, istri yang kehilangan suami, ibu yang kehilangan anak. Lalu, bagaimana mungkin luka itu sembuh jika mesin yang menciptakannya dibiarkan beroperasi tanpa henti?
Teori Dependency yang dikemukakan Paul Pierson dan Mahoney menjelaskan bahwa institusi yang sudah terjebak dalam jalur sejarah buruk cenderung mengulang pola lama. Inilah yang kita lihat dari Polri hari ini: dari masa ke masa, pola represifitas, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan selalu kembali, seakan terjebak dalam lingkaran setan. Dan Karl Marx, dengan teori Revolusi Sosial-nya, pernah mengingatkan: setiap kali kekuasaan yang menindas rakyat dibiarkan tumbuh, maka rakyatlah yang akhirnya dipaksa mengambil jalan revolusi sebagai bentuk pembebasan.
Tentu, kita tidak ingin bangsa ini terseret pada jalan berdarah itu. Kita tidak ingin Indonesia terjerumus pada kekacauan hanya karena institusi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi sumber ketakutan. Karena itu, moratorium bisa menjadi jalan tengah: tidak gegabah membubarkan, tidak pula pasrah membiarkan. Sebuah kesempatan untuk menata ulang relasi kuasa, agar Polri benar-benar kembali pada hakikatnya: menjadi pelindung dan pengayom rakyat.
Pada akhirnya, refleksi ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam: bagaimana wajah negeri ini kelak, jika aparat yang mestinya menjaga justru menakutkan rakyatnya sendiri? Apakah kita berani menekan rem darurat itu, ataukah kita akan membiarkan kereta ini terus melaju hingga jurang?
Dan, kita semua sadar: negara ini bukan milik institusi, bukan milik kekuasaan, bukan milik senjata. Ia milik rakyat. Dan rakyatlah yang menjadi alasan mengapa negeri ini berdiri. Maka, seharusnya, aparat yang lahir dari rakyat tidak boleh berbalik arah melawan rakyatnya sendiri.
Kita semua berdoa, semoga luka-luka yang ditinggalkan hari ini menjadi pengingat untuk esok. Semoga negeri ini kelak menemukan jalan menuju kepolisian yang benar-benar berpihak pada keadilan, bukan pada kuasa yang membabi buta. Semoga para pemimpin berani menimbang ulang arah, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keberanian moral untuk berbenah.
Dan akhirnya, semoga Indonesia terus melangkah maju—bukan sekadar menjadi negara yang kaya, bukan sekadar negara yang besar, melainkan negara yang benar-benar merdeka, karena rakyatnya hidup dengan aman, damai, dan bermartabat.
Negara lahir dari rakyat, tumbuh karena rakyat, dan runtuh bila meninggalkan rakyat.
Tulisan ini saya persembahkan untuk almarhum Affan Kurniawan, seorang pemuda 21 tahun, driver ojek online, korban kekerasan Polri. Semoga namamu menjadi pengingat bagi bangsa ini: bahwa satu nyawa rakyat selalu lebih berharga daripada seribu tameng kekuasaan.
Oleh: Kafabihi
Manajer Sekolah Kita Menulis Cabang Tanjungpinang.
Berita Terkait
Mungkin anda suka
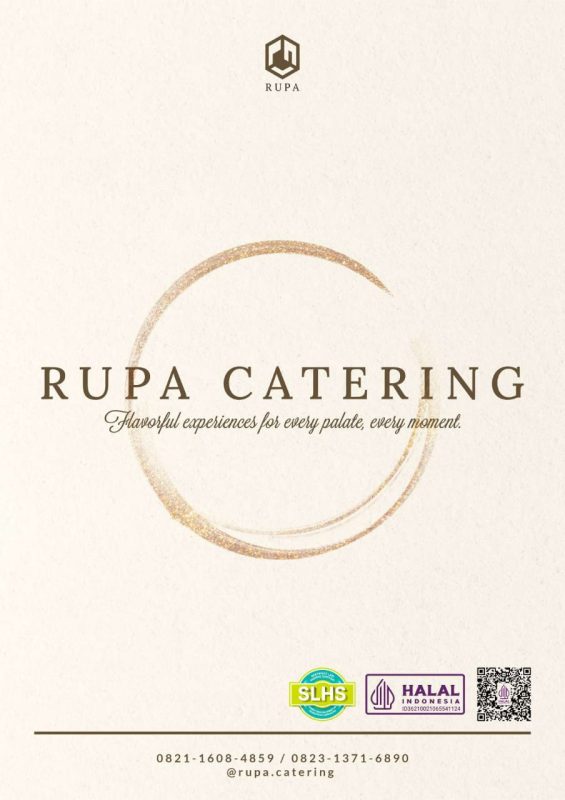
Terpopuler















