
Mudy Taylor dan Royalti Lagu: Suara Tertawa yang Menginginkan Damai
Oleh: Diaz

Mudy Taylor dan Royalti Lagu: Suara Tertawa yang Menginginkan Damai
Ratas, — Dalam belantara dunia hiburan Indonesia, nama Mudy Taylor mungkin tak segemerlap musisi papan atas atau komika yang kerap muncul di layar kaca nasional. Namun, di lingkaran seniman kreatif, ia dikenal sebagai sosok unik—komika, pemusik, penulis lagu parodi, dan pengamat sosial yang menyelipkan kritik tajam dalam balutan tawa. Gaya jenakanya absurd, sarkastik, namun reflektif. Lebih dari sekadar pelawak, Mudy adalah seniman multi-talenta yang menjadikan musik sebagai bagian tak terpisahkan dari komedinya.
Belakangan, Mudy terlihat bergabung dalam manajemen V Corps yang digawangi Virza, mantan vokalis Dewa 19. “Ya, saat ini saya juga bersama manajemen Virza Idol,” ujar Mudy saat dihubungi wartawan via sambungan telepon dari Jakarta (20/6/2025). Dalam manajemen yang bermarkas di Bintaro Sektor 9, Tangerang, turut bergabung juga Kiki “The Potters”, yang baru-baru ini ikut meramaikan peluncuran kafe DiWaroeng milik Virza.
Di tengah menghangatnya isu royalti lagu dan hak cipta—terutama setelah sejumlah musisi terlibat konflik terbuka—Mudy Taylor memilih menyuarakan perspektif dari sudut yang berbeda. Dengan gaya khasnya yang santai namun penuh makna, ia menyampaikan keprihatinan atas situasi ini.
“Soalnya tagihan royaltinya nggak main-main harganya… wkwk,” kelakarnya. Namun di balik tawa itu, tersimpan kegelisahan akan aturan yang kaku, yang menurutnya bisa mematikan kreativitas, khususnya bagi para komika yang kerap memanfaatkan musik dalam pertunjukan mereka.
“Khusus untuk seniman komedi, mohon dilupakan dulu soal royalti. Malah, kalau bisa disupport untuk bikin kompilasi lagu-lagu mereka agar tak lekang dimakan waktu,” ujarnya. Mudy mencontohkan lagu-lagu anak seperti “Pelangi-Pelangi”, “Potong Bebek Angsa”, dan “Balonku”, yang kerap diolah ulang menjadi parodi segar dan justru membuat lagu-lagu tersebut tetap hidup lintas generasi.
Bagi Mudy, kunci dari perdebatan royalti ini adalah kejelasan niat—antara penggunaan non-komersial dan komersial. “Kalau mereka cover dan cuma buat tampil biasa, ya biarin aja. Asal nyebut sumber lagunya. Tapi kalau udah masuk ranah komersial, misalnya buat iklan, ya memang harus bayar royalti. Fair aja,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Mudy juga menyampaikan pesan kepada para pembuat kebijakan dan pelaku industri. Ia mengimbau agar persoalan royalti tidak dibahas dengan emosi. “Mohon dibicarakan baik-baik dengan para pencipta lagu. Jangan keras atau arogan. Sesama seniman, mari duduk dalam suasana yang tenteram, agar semua paham dan selesai tanpa dendam,” katanya.
Ia turut menyinggung konflik antar musisi yang belakangan mencuat, seperti yang terjadi di lingkup Dewa 19. Menurutnya, pertikaian semacam itu justru memperburuk citra dunia musik di mata publik.
Dengan nada ringan tapi sarat makna, Mudy Taylor memberi warna berbeda dalam diskusi royalti—bukan sebagai pihak yang menuntut atau membela diri, melainkan sebagai seniman yang mengajak untuk duduk bersama, membahas hak dan etika seni dalam semangat damai.
“Nanti kalau ada perkembangan, saya kasih saran lagi… hehehe, bercanda,” tutupnya, tentu saja dengan tawa.
Di tengah dunia seni yang makin keras memperdebatkan hak, suara seperti Mudy Taylor menjadi pengingat: bahwa seni sejatinya lahir dari niat berbagi, menyatukan manusia lewat karya. Sebelum segala menjadi perkara hukum, barangkali yang dibutuhkan hanyalah—sedikit tawa, sedikit empati, dan ruang bicara yang tenang di antara sesama seniman.
Berita Terkait
- RETAS 4,9 JUTA DATA NASABAH BANK, HACKER “BJORKA” DITANGKAP POLDA METRO JAYA
- Badan Pemulihan Aset Lelang Barang Rampasan Negara Senilai Rp 2,7 Miliar dalam Perkara Korupsi dan TPPU Terpidana Harry Prasetyo
- Anomali Pidana Pada Tindak Pidana Inses, Disebut Sebagai Kejahatan Serius yang Bisa Dipenjara Hanya 1 (satu) Hari
- Pergulatan Pemberlakuan KUHP Nasional
- BNN dan Polri Perkuat Sinergi, Ungkap 1,7 Ton Narkotika di Sumut dan Aceh
Mungkin anda suka
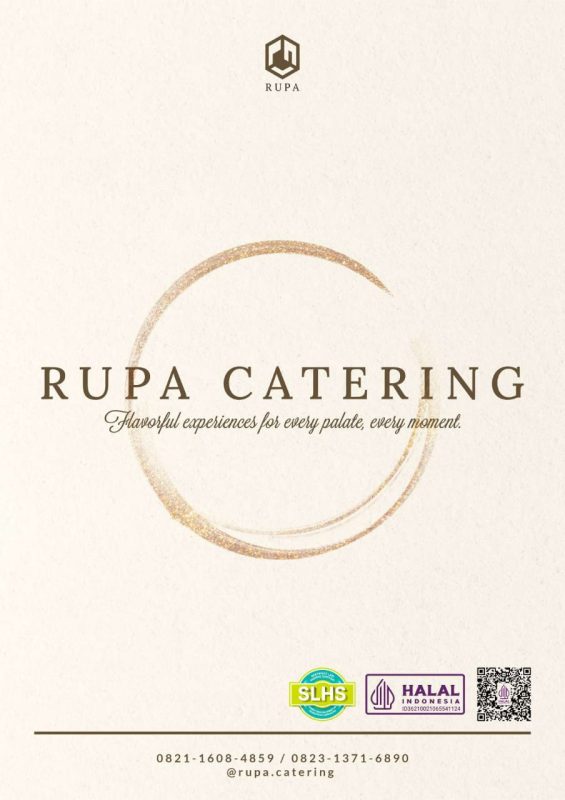
Terpopuler















