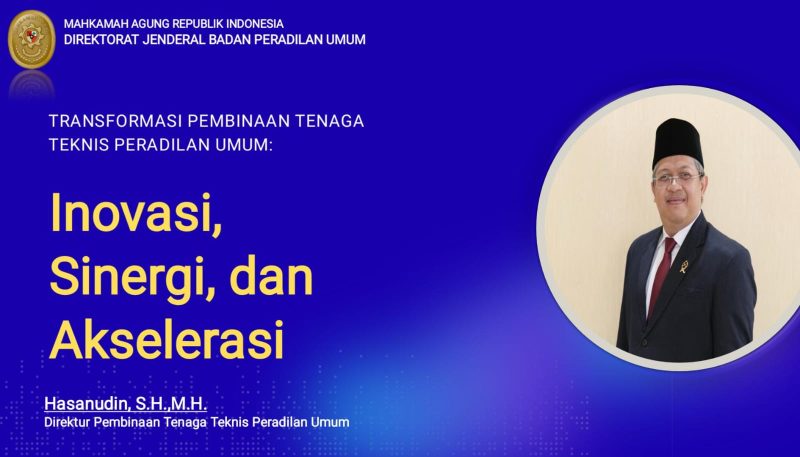Korupsi Wakil Menteri, Antara Retorika dan Luka Kolektif
Oleh: Diaz

Korupsi Wakil Menteri, Antara Retorika dan Luka Kolektif
RATASTV – Kamis malam, 21 Agustus 2025, publik dikejutkan dengan kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Ia ditangkap atas dugaan pemerasan terkait penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebuah instrumen vital yang semestinya melindungi nyawa para buruh di tempat kerja. Kasus ini bukan hanya menyentuh persoalan hukum, tetapi juga menelanjangi moralitas kekuasaan: bahwa korupsi masih hidup subur bahkan di ruang-ruang yang seharusnya menjaga keselamatan manusia.
Sontak, pernyataan “zero tolerance” terhadap korupsi yang digaungkan Menteri Ketenagakerjaan maupun Presiden Prabowo Subianto diuji keras. Bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi, yang duduk hanya satu tingkat di bawah menteri, tega menjadikan sertifikasi K3 sebagai lahan pungli? Bukankah ini sama saja dengan memperdagangkan keselamatan rakyat demi keuntungan pribadi? Luka kolektif itu makin dalam karena publik sadar, yang diuntungkan hanyalah segelintir orang, sedangkan yang dikorbankan adalah buruh dan masyarakat luas.
Korupsi yang Berulang: Dari Kabinet Jokowi ke Kabinet Prabowo
Kasus Immanuel Ebenezer seolah menjadi pengulangan kisah lama. Pada periode Presiden Joko Widodo, publik juga dikecewakan dengan penangkapan sejumlah pejabat tinggi: Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan), Juliari Batubara (Menteri Sosial), hingga Johnny G. Plate (Menkominfo). Kini, di periode awal pemerintahan Prabowo, sejarah itu kembali berulang.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah masalahnya terletak pada individu yang serakah, ataukah pada sistem politik dan birokrasi yang memang subur dengan peluang korupsi? Jika setiap rezim selalu menghasilkan pejabat yang terjerat korupsi, maka jelas bahwa akar masalahnya lebih dalam dari sekadar perilaku personal. Ia telah menjadi budaya yang dilegalkan oleh sistem patronase politik, biaya tinggi dalam kontestasi, serta lemahnya kontrol kelembagaan.
Luka Nyata: Menjual Keselamatan Buruh
Ironi terbesar dalam kasus ini adalah objek korupsinya: sertifikat K3. Seharusnya sertifikasi ini menjamin bahwa perusahaan mematuhi standar keselamatan kerja, sehingga buruh dapat bekerja dengan aman dan layak. Namun ketika sertifikat ini justru diperdagangkan, keselamatan buruh menjadi taruhannya.
Korupsi di ranah K3 bukanlah sekadar pelanggaran administratif. Ia adalah pengkhianatan moral karena memperdagangkan nyawa manusia. Seorang buruh yang terjebak dalam lingkungan kerja berbahaya tanpa standar keselamatan adalah korban langsung dari praktik busuk ini. Maka kasus ini tidak bisa dilihat hanya sebagai “penyalahgunaan jabatan”, melainkan kejahatan kemanusiaan yang merusak keadilan sosial.
Krisis Kepercayaan Publik
Setiap kali terjadi OTT terhadap pejabat tinggi, publik terombang-ambing antara harapan dan kekecewaan. Harapan karena penegakan hukum masih bekerja kekecewaan karena lagi-lagi korupsi dilakukan oleh pejabat yang dipercaya mengelola urusan rakyat.
Kasus ini bisa menjadi pukulan telak terhadap legitimasi pemerintahan Prabowo. Bagaimana mungkin pemerintah meyakinkan publik tentang komitmen pemberantasan korupsi, jika pejabat di lingkaran inti kekuasaan justru terjerat? Apalagi, di saat bersamaan, publik juga menyaksikan praktik pengampunan terhadap pejabat lain yang bermasalah, seperti dalam kasus mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Kontradiksi ini menimbulkan kesan bahwa pemberantasan korupsi sering kali hanya menjadi alat politik: tegas pada lawan, tapi lunak pada kawan.
Dari Retorika ke Aksi Nyata
Pernyataan “tidak ada yang kebal hukum” harus dibuktikan dengan konsistensi, bukan sekadar jargon. Pemerintah tidak boleh berhenti pada sikap simbolik, misalnya sekadar mencopot jabatan atau menyampaikan pernyataan keras. Lebih dari itu, dibutuhkan reformasi sistemik: memperbaiki tata kelola, memperkuat transparansi, serta mempersempit ruang intervensi politik dalam birokrasi.
Di sisi lain, publik juga harus sadar bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada KPK atau aparat hukum. Peran masyarakat sipil, media, dan dunia akademik sangat penting untuk terus mengawasi, mengkritik, dan menolak normalisasi korupsi. Sebab bahaya terbesar dari korupsi adalah ketika ia dianggap lumrah dan “biasa saja”.
Alarm yang Tidak Boleh Diabaikan
OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan seharusnya menjadi alarm keras bagi bangsa ini. Jika korupsi sudah menyentuh ruang vital yang menyangkut keselamatan buruh, maka sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga nyawa manusia.
Pemerintah harus membuktikan bahwa slogan “zero tolerance” bukan sekadar retorika politik. Kasus ini bisa menjadi momentum pembuktian apakah pemerintahan benar-benar berani membersihkan diri, atau justru menambah daftar panjang kegagalan dalam perang melawan korupsi.
Pada akhirnya, melawan korupsi adalah melawan kebiasaan buruk yang diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya. Dan jika bangsa ini benar-benar ingin mencapai cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045, maka korupsi harus dihentikan sekarang juga bukan besok, bukan lusa, apalagi setelah semua terlambat.
Oleh Aulia Halsa SH
Berita Terkait
Mungkin anda suka
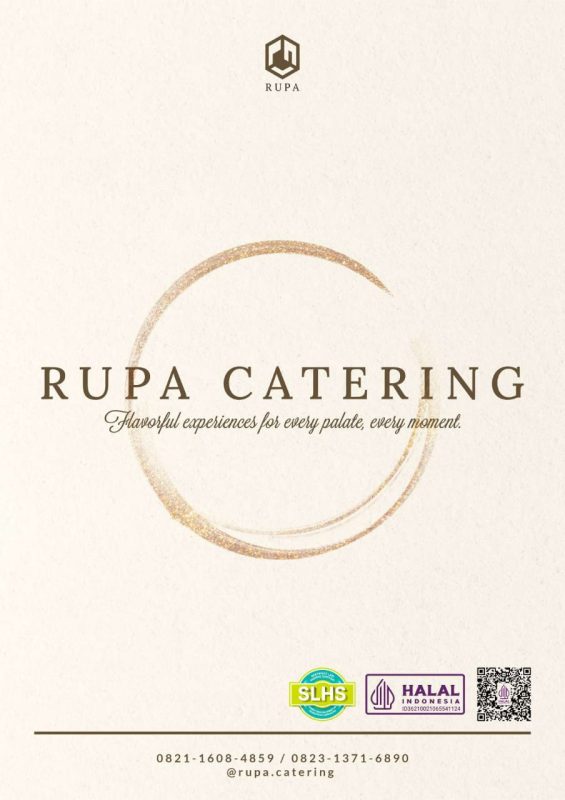
Terpopuler